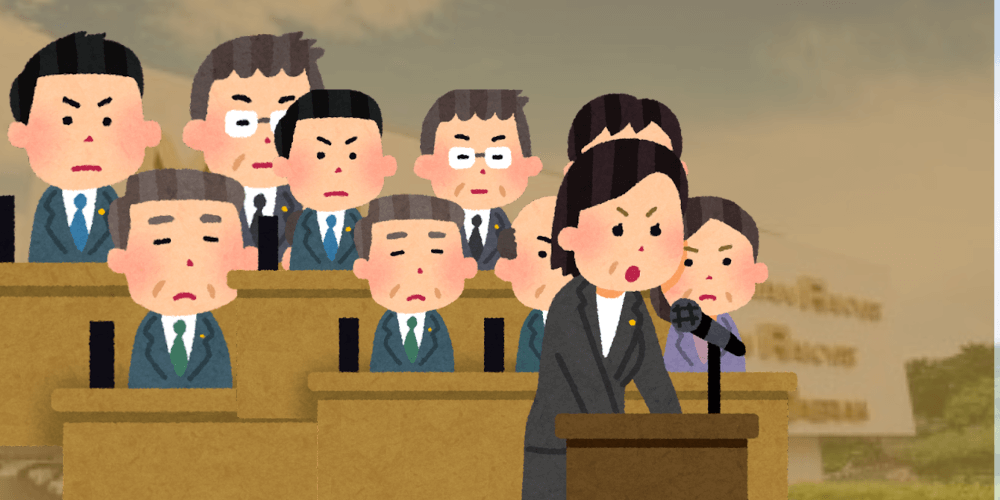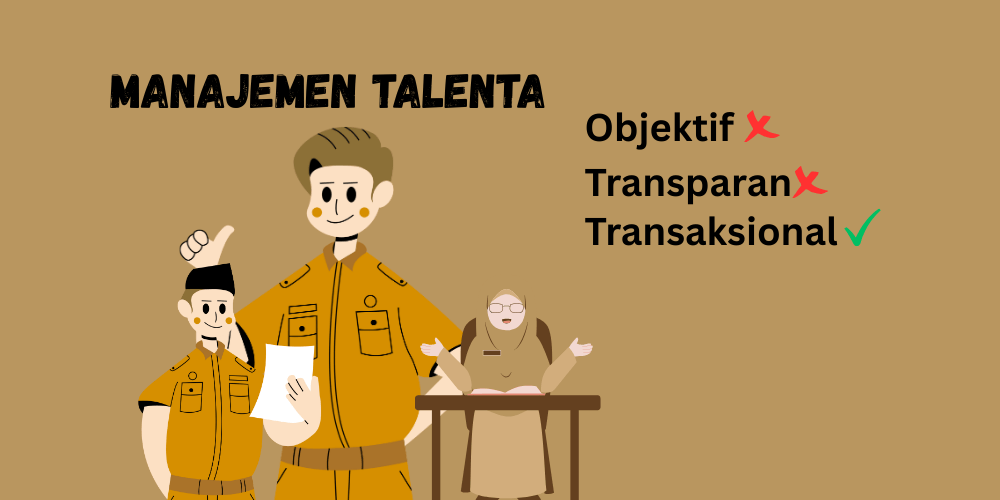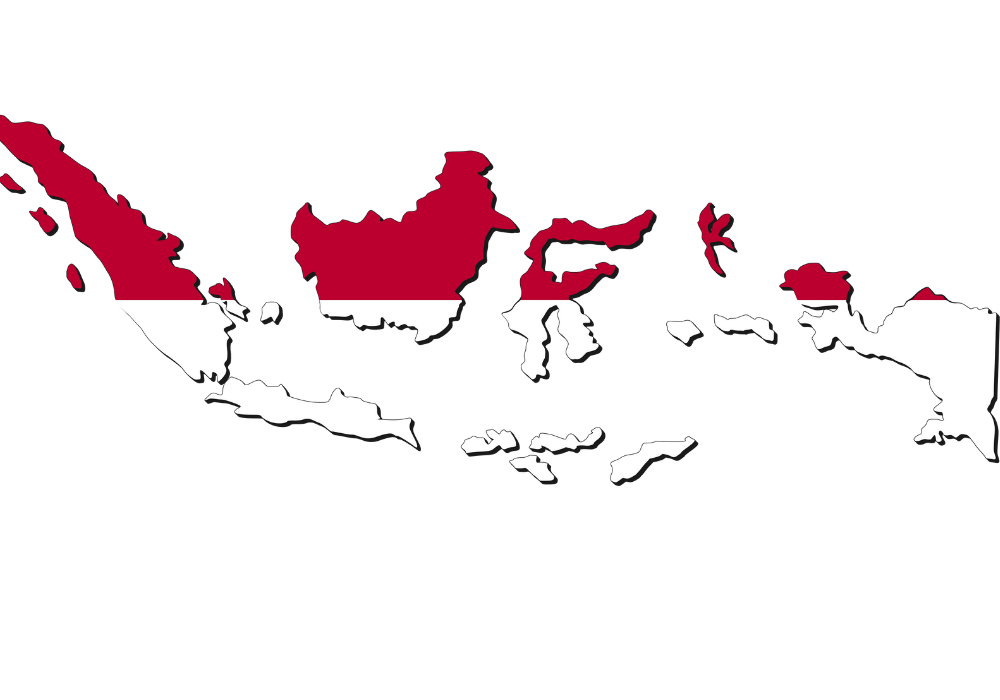Paradoks Koperasi: Ketika Jalan Rakyat Dikooptasi Oligarki

Oleh Ahmad Djarkoni, Warga Banten
Di tengah kesulitan ekonomi yang makin mencekik, banyak suara publik yang bertanya: di mana sebenarnya uang kita berputar? Di pasar, uang habis untuk barang impor dan korporasi digital asing. Di bank, dana rakyat disalurkan untuk konglomerat. Di negara, anggaran publik kembali lagi ke elit lewat proyek dan konsesi. Maka, ketika sebagian orang menyerukan agar rakyat “ambil alih ekonomi” lewat koperasi, pertanyaan berikutnya pun muncul: apakah koperasi masih bisa dipercaya?
Kita tentu ingat cita-cita Bung Hatta, koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Ia membayangkan sistem ekonomi yang dikelola rakyat untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk akumulasi segelintir orang. Namun, tujuh dekade setelah proklamasi, semangat itu tinggal jargon di spanduk perayaan Hari Koperasi. Di lapangan, banyak koperasi berubah menjadi versi mini dari korporasi predator: tertutup, elitis, dan rawan korupsi.
Krisis Kepercayaan Ekonomi Rakyat
Akar dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sebenarnya beralasan. Rakyat kecil sulit mengakses pinjaman bank karena tidak punya jaminan. Sementara di sisi lain, korporasi besar dengan mudah memperoleh kredit triliunan. Ketimpangan akses modal inilah yang membuat ekonomi rakyat terjebak pada lingkar kemiskinan yang tidak kunjung putus.
Sayangnya, ketika koperasi muncul sebagai alternatif, banyak yang justru tumbang karena salah urus atau diselewengkan pengurusnya. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, dari lebih dari 127 ribu koperasi yang terdaftar, hampir separuhnya tidak aktif. Banyak yang tutup karena masalah manajemen, konflik internal, atau korupsi dana anggota.
Kasus-kasus koperasi bermasalah seperti KSP Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, dan beberapa koperasi pegawai di instansi pemerintah telah menimbulkan trauma kolektif. Rakyat yang sudah susah menabung malah kehilangan simpanannya. Akibatnya, koperasi kehilangan makna sebagai simbol solidaritas ekonomi, berubah menjadi instrumen rente baru.
Paradoks: Dari Alat Perlawanan ke Alat Kekuasaan
Paradoks terbesar ekonomi rakyat di Indonesia terletak di sini: instrumen yang seharusnya membebaskan rakyat justru terkooptasi oleh logika kekuasaan dan rente. Banyak koperasi yang lahir bukan dari kebutuhan ekonomi warga, tetapi dari proyek politik dan program pemerintah. Akibatnya, koperasi menjadi “badan usaha formalitas” untuk menyerap dana bantuan, bukan organisasi demokratis yang mengatur ekonomi bersama.
Fenomena ini tak lepas dari patronase politik. Di tingkat lokal, pengurus koperasi sering adalah orang yang dekat dengan pejabat, aparat, atau partai politik. Rapat anggota tahunan jarang dilaksanakan, laporan keuangan tak diaudit, dan anggota hanya dijadikan nama di daftar. Demokrasi ekonomi mati di tangan elit kecil yang memonopoli keputusan.
Lebih ironis lagi, beberapa koperasi besar justru menjadi “alat investasi” elite yang mencari legitimasi moral. Mereka menggunakan kata “koperasi” agar terlihat pro-rakyat, padahal model bisnisnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan finansial biasa. Di titik ini, koperasi berhenti menjadi alat perlawanan terhadap kapitalisme, dan malah menjadi subkontraktor dari sistem yang ingin ia lawan.
Kegagalan Tata Kelola dan Budaya Transparansi
Masalah koperasi bukan hanya soal niat buruk segelintir orang, tetapi juga kegagalan sistemik dalam tata kelola. Regulasi koperasi di Indonesia masih lemah dan ketinggalan zaman. Pemerintah cenderung fokus pada jumlah koperasi, bukan kualitas kelembagaannya. Tak ada sistem pengawasan yang independen dan profesional. Akibatnya, koperasi rawan disalahgunakan, apalagi ketika dana bantuan pemerintah ikut bermain.
Baca juga Manajemen Talenta, Mau Ideal atau Transaksional?
Masalah lain adalah budaya ekonomi kita sendiri. Koperasi yang ideal menuntut transparansi dan partisipasi aktif anggota. Tapi di banyak tempat, transparansi dianggap “tidak sopan” karena bisa menyinggung pengurus. Relasi sosial yang paternalistik membuat anggota segan mengkritik. Inilah yang membuat moral hazard tumbuh subur.
Mencari Jalan Keluar: Reformasi Koperasi Pro-Rakyat
Kalau begitu, apakah koperasi masih layak diandalkan? Jawabannya: ya, tetapi dengan syarat harus direformasi secara radikal.
Pertama, koperasi harus kembali ke prinsip dasarnya: transparansi dan demokrasi ekonomi.
Teknologi digital bisa menjadi alat bantu efektif. Koperasi generasi baru bisa memakai sistem pencatatan terbuka: laporan keuangan diunggah rutin, setiap anggota bisa memantau kas secara real-time. Praktik seperti ini sudah dilakukan beberapa komunitas, misalnya koperasi petani di Jawa Tengah dan koperasi digital Arisan Mapan. Model semacam itu menumbuhkan kepercayaan karena akuntabilitasnya langsung ke anggota, bukan ke pemerintah.
Kedua, audit publik wajib untuk semua koperasi penerima dana pemerintah. Audit ini tidak harus rumit; cukup berbasis standar sederhana dan dilakukan oleh lembaga independen. Publik berhak tahu ke mana perginya dana bantuan ekonomi rakyat. Jika koperasi memang untuk rakyat, maka tak ada alasan menutup-nutupi laporan.
Ketiga, pendidikan ekonomi rakyat harus menjadi agenda utama. Banyak koperasi gagal bukan karena korupsi, tapi karena anggota tidak paham fungsi koperasi. Mereka menganggap koperasi sekadar tempat pinjam uang, bukan wadah membangun kesejahteraan kolektif. Pendidikan ekonomi berbasis komunitas — seperti pelatihan pencatatan, etika pengelolaan, dan partisipasi anggota, bisa menjadi benteng pertama melawan penyimpangan.
Keempat, hubungkan koperasi dengan ekosistem ekonomi lokal.
Koperasi sebaiknya menjadi simpul rantai pasok antara petani, nelayan, UMKM, dan pasar lokal. Dengan begitu, ia tak lagi sekadar lembaga keuangan, tapi bagian dari sistem produksi dan distribusi ekonomi rakyat. Model seperti ini terbukti efektif di beberapa daerah, misalnya koperasi pertanian di Bali dan koperasi perikanan di Maluku.
Mengembalikan Koperasi ke Akar Politiknya
Koperasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga instrumen politik rakyat. Ia lahir dari gagasan bahwa kekuasaan ekonomi harus tersebar, bukan terkonsentrasi. Karena itu, revitalisasi koperasi tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek teknis, ini adalah perjuangan politik untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi dari tangan oligarki.
Pemerintah perlu berhenti memperlakukan koperasi sebagai angka statistik. Yang dibutuhkan bukan seremonial peresmian, tapi politik keberpihakan: kebijakan fiskal yang mendukung koperasi produksi rakyat, pengawasan yang independen, serta perlindungan hukum bagi anggota yang berani bersuara.
Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil juga perlu membangun koperasi tandingan — koperasi kecil tapi jujur, transparan, dan terbuka untuk diaudit siapa pun. Justru dari inisiatif seperti inilah harapan bisa lahir: membuktikan bahwa koperasi masih mungkin menjadi ruang demokrasi ekonomi di tengah gurita oligarki.
Membangun Kembali Kepercayaan
Kita tidak bisa menuntut rakyat percaya pada sistem ekonomi rakyat jika lembaga rakyat sendiri tidak bisa dipercaya. Karena itu, membenahi koperasi bukan hanya soal keuangan, tapi soal moral politik. Selama koperasi masih dikuasai oleh mental rente dan patronase, maka koperasi akan tetap menjadi nama lain dari kapitalisme lokal.
Namun jika koperasi kembali ke ruh aslinya, dikelola secara jujur, terbuka, dan partisipatif, maka di sanalah jalan baru kedaulatan ekonomi rakyat bisa dibangun.
Di tengah krisis ekonomi dan ketidakadilan struktural, koperasi bisa menjadi ruang kecil untuk membuktikan bahwa ekonomi rakyat bukan mitos, tapi pilihan politik yang bisa diwujudkan. (***)